
Sore itu baru jam 15.30. Tapi tak terbayang panasnya terik matahari, seperti bara tungku yang diletakkan tepat di atas kepalaku, saat aku baru saja turun dari bus kota dan berjalan menelusuri terotoar gersang, diselingi deru mobil dan bau asap knalpot yg keluar dari kendaraan bermesin diesel.
Di pinggir jalan ada pedagang es degan yang dikerumuni oleh beberapa wanita berpayung yg sepertinya sudah tak tahan lg dg panasnya inti tatasurya yg mendera itu, sementara disebelah pedagang es degan, si tukang bakso cuma berdiri manyun dgn sedikit melongo, bak pungguk merindukan bulan, wajahnya menyiratkan iba yg mendalam karena tidak seorangpun yg menghendaki dagangannya, semua wanita merubung si penjual es degan.
Sambil terus berjalan aku berpikir seandainya aku berhenti sebentar dan membeli satu gelas saja nikmatnya minuman kesayanganku itu, pasti rasanya akan sangat nikmat, bagai menemukan oase di tengah panasnya gurun pasir. Tapi entah kenapa, kakiku rasanya tidak se ide dengan pikiranku, aku terus berjalan dengan satu tujuan..pulang.
Setiap aku pulang kantor, si kecilku, Aisha, punya cara tersendiri untuk mendinginkan kepalaku dan menarik perhatianku agar, paling tidak, segera menyapanya terlebih dulu sebelum aku melakukan hal-hal lain. Misalnya ia akan menatapku dengan tatapan lucu khas seorang bayi atau ia akan buru-buru berlari menghampiriku sambil mulut mungilnya berkata dengan gaya lucu, “pappap..pappap…”. Tentu saja aku jadi tak tega untuk melewatkannya sejenak, bahkan untuk lebih dulu menyapa ibu mertuaku yang menjaganya setiap aku ke kantor.
Bahkan bayi empat belas bulanku itu tampaknya sudah mengerti sekali kalau aku hanya punya ‘waktu terbatas’ untuknya. Setiap pagi sebelum aku berangkat atau saat aku sedang libur, ia akan dengan maksimal menggunakannya untuk menarik perhatianku dengan kemanjaan dan gaya bayinya yang lucu dan menggemaskan.
Tak jarang, bila ia sedang kelewat manja dan nyaris tak mau ditinggal sedikitpun meski hanya untuk sekedar menyeruput kopiku, ia akan menangis menjerit-jerit hanya untuk ‘urusan sepele’ seperti itu. Tentu saja ini cukup menjengkelkan bagiku yang kadang menjadi sedikit marah padanya.
Tapi segera aku beristighfar manakala aku melihat wajahnya yang polos dan sikap pemaafnya. Terkadang ia balas marah padaku, tapi lebih sering ia ‘memaafkanku’ dengan gayanya yang sangat bayi pula. Biasanya ia akan menatapku lekat dan mengusapkan tangan-tangan mungilnya di wajahku lalu mengeluarkan kekeh lucunya, “Hehe…hehe…” atau sapaan khasnya, “Ngg…guu..guu…” atau bahkan ia seakan minta maaf dengan lucu, “Mbuuu…aaapp…appp,”
Siapa yang tega untuk terus marah padanya? Maka jadilah aku minta maaf padanya dan memeluknya erat-erat. Bahkan malamnya pun, jika tidur, saat dia berada di tengah antara aku dengan istriku, Aisha sering sekali memeluk tanganku erat-erat, melepaskan pelukan dari mamanya yg terlelap kecapaian setelah kerja lembur sampai malam.
Anak kita memiliki pertalian jiwa dan darah dengan kita. Maka ia adalah bagian dari hidup kita. Ia butuh senantiasa dekat dengan kita, bahkan hingga saat ia dewasa kelak. Ia butuh menyatukan hati dan perasaannya dengan kita. Itulah sebabnya ia meminta sedikit saja waktu dari kita untuk tempatnya bermanja.
Bagi kita yang terbiasa sibuk dan bekerja sepanjang minggu, mungkin sering menggunakan ungkapan ‘apologia’, yang penting kualitas dan bukan kuantitas. Atau kita lebih percaya dengan pola asuh ‘remote parenting’. Akupun tadinya demikian. Tetapi sikap Aisha yang pemaaf justru mengajarkanku sesuatu.
Bahwa kualitas nyaris tak bisa diwujudkan jika kuantitas yang ada pun tidak termanfaatkan secara optimal. Mana ada kualitas jika kita pulang ke rumah dalam keadaan capek dan masih harus mengerjakan sederet tugas rumah tangga lain, bagi seorang wanita seperti memasak untuk makan malam, cuci piring, bebenah, dan hingga tetek bengek lain, dan bagi sang suami, jika malah membawa tugas kantor pulang ke rumah, dan harus segera kelar besok paginya untuk dipresentasikan, yang membuat si kecil menjadi prioritas nomor sekian setelah tugas-tugas tersebut?
Bahwa remote parenting nyaris tak berbunyi apapun kecuali jika sebelumnya antara anak, ibu dan ayah telah terjalin ikatan yang cukup erat dalam rentang waktu yang bisa mereka lalui bersama. Dan, bahwa si kecil selalu bersangka baik pada setiap jenak kesibukan ibundanya dan ayahandanya tercinta , bahkan meskipun kesibukan itu membuatnya ‘dekat di mata tapi jauh di hati’ dengan mereka. Si kecil yang polos itu tak bisa mendendam meski untuk sebuah haknya yang paling asasi yang telah terampas secara tidak sengaja oleh kesibukan misalnya, minum kopi.
Bukan berarti kita hanya harus melewatkan waktu bersama si kecil sementara yang lain terabaikan, tapi mungkin, cara pemanfaatannya yang harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun yang terbengkalai. Masalahnya jika ini berkaitan dengan hak anak yang terampas, bukan mustahil suatu saat di masa depan ia akan tumbuh menjadi pribadi yang ‘tidak paripurna’ kematangannya.
Atau bisa jadi ia akan melampiaskan ‘dendam masa kecilnya’ kepada anaknya kelak secara berlebihan. Anak kita adalah sebuah wajah bersih tentang masa depan sebuah kualitas makro. Maka kitapun sangat punya andil maha penting untuk turut mengisi kepribadiannya.
Seperti yg ditulis dalam bukunya Darmanto Jatman “Terima Kasih Indonesia” yang disusun bersama dengan Adriani S Soemantri. Ia berkata dalam salah satu tulisannya di buku tersebut, pendidikan anak kita laksana sebuah mosaik. Kita hanya merekatkan sepotong, nanti lingkungan yang akan membantu merekatkan yang lainnya pula hingga jadi sebuah mosaik yang indah.
Dan saya rasa meletakkan potongan-potongan mosaik ini perlu dilakukan secermat dan sehati-hati mungkin, karena begitu banyak unsur yang terkait di dalamnya. Demikian pula, kitalah yang akan sangat menentukan, potongan mosaik yang mana lagikah yang cocok bagi jiwa anak kita agar sempurna ia menjadi sebuah lukisan mosaik yang elok.
Maka waktu untuk anak kita bermanja adalah juga saat yang tepat untuk merekatkan potongan mosaik itu agar kelak menjadilah ia generasi Robbani yang cerdas, shalih, berdaya guna, sehat, dan matang. Saya rasa, betapa menyesalnya saya atas waktu-waktu yang telah terlalui begitu saja dengan amarah saya untuk si kecil Aisha.
Maafkan papap ya, nak, yang tak mengerti bahwa sebenarnya kamu sedang meminta pada papap, “Papapp, maukah mbu sedikit saja menolongku untuk merekatkan sepotong saja mosaik dalam hidupku. Agar kelak aku benar-benar bisa membanggakan bagi Papap dan Mamam?”
Maafkan papap dan mamam, cintaku….
inspired by Ummu Akna
Aisha..
Diposting oleh
Agus Fitrianto, SPt
![]()
![]()
Label: Motivasi Kisah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



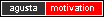
Comment Form under post in blogger/blogspot